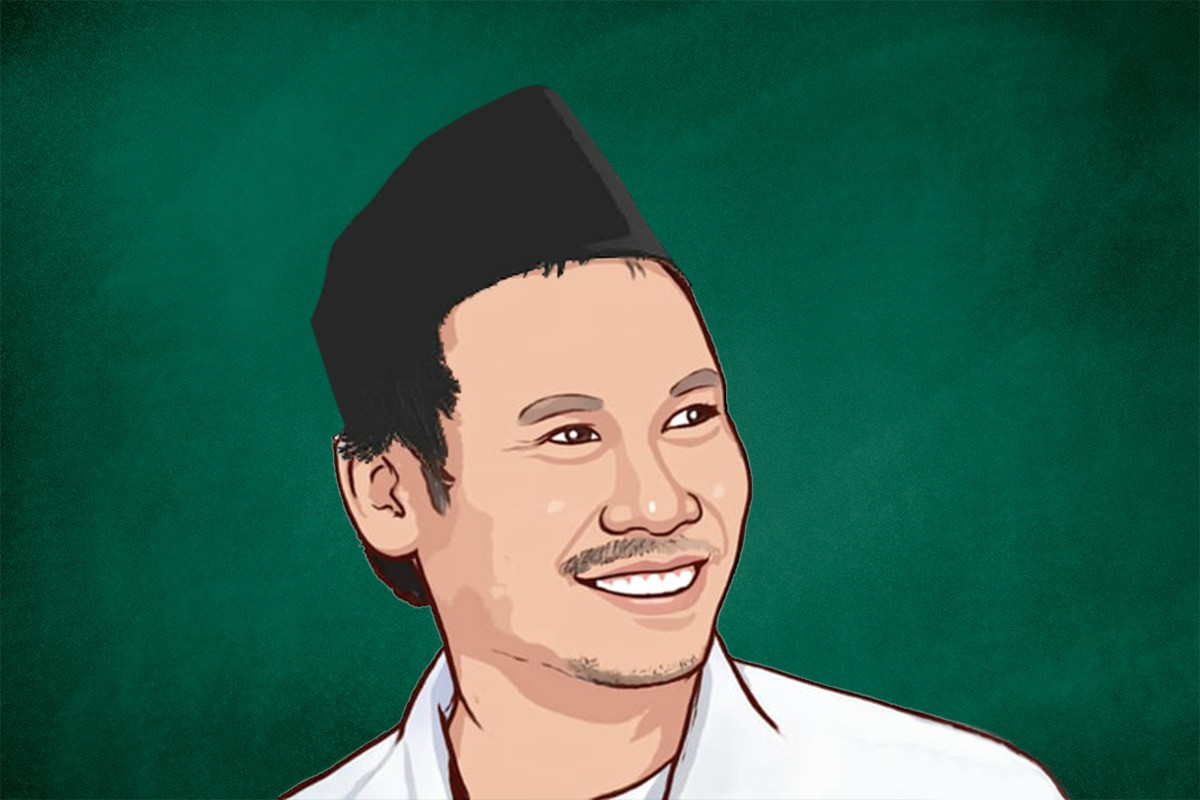PASURUAN – Dalam sebuah tausiyah yang mencerahkan, ulama kenamaan KH Bahaudin Nursalim atau yang akrab disapa Gus Baha mengajak umat untuk merenungi kembali esensi kebahagiaan hakiki dalam Islam serta bagaimana mengelola nafsu agar tidak terjerumus pada perilaku yang merugikan. Beliau menyoroti bahaya pola pikir yang dikendalikan oleh hawa nafsu, sebagaimana dikritik Al-Qur’an terhadap mereka yang mempertuhankan keinginan pribadinya. Ini berbeda dengan generasi Nabi, sahabat, dan para ulama terdahulu yang memiliki pola pikir yang jernih, sederhana, dan berlandaskan tauhid. Jum’at, 11 Juli 2025
Makna Kebahagiaan dalam Ketaatan
Gus Baha menekankan bahwa Rasulullah SAW senantiasa membawa kegembiraan.
“Bergembiralah wahai kaum Muslimin, Allah telah membuka pintu langit yang sebelumnya tidak pernah dibuka, dan Allah membanggakanmu di hadapan para malaikat-Nya,” kutip beliau.
Menurut Gus Baha, resep sederhana agar senantiasa berada dalam jalan kebaikan—bahkan hingga akhir hayat—terletak pada prinsip:
“Addu faridhatan wantadhiru ukhra”
(Lakukan satu kewajiban, lalu tunggulah kewajiban berikutnya).
Artinya, setelah shalat Subuh, niatkan untuk menanti shalat Dzuhur, dan seterusnya.
“Dengan begitu, status kita di dunia adalah penunggu ibadah, bukan penunggu kekayaan atau kemapanan yang dikendalikan oleh nafsu,” jelas beliau.
Hidup seorang Muslim, lanjut Gus Baha, seyogyanya adalah perjalanan dari satu kebaikan ke kebaikan lain—sejalan dengan pesan Allah dalam QS. Al-Insyirah:
“Fa idza faraghta fanshab”
(Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain).
Gus Baha juga mengingatkan bahaya mentalitas “belum mau mati sebelum kaya atau membalas dendam”, yang justru bisa menyebabkan seseorang wafat dalam keadaan hasud. Sebaliknya, menjadi fakir justru bisa menjadi sebab ringannya hisab di akhirat.
“Islam itu menjaga kebahagiaan,” tegasnya.
Kebahagiaan dalam Islam bukanlah kesenangan sesaat yang diraih lewat maksiat, tetapi kedamaian yang lahir dari ketaatan. Ciri utama wali Allah adalah bebas dari rasa takut dan sedih:
“Ala inna auliya Allahi la khaufun ‘alaihim wa laa hum yahzanun.”
Ulama terdahulu dikenal hidup dengan sangat rileks, menghadapi pujian maupun cercaan dengan santai. Bahkan pernyataan masyhur Imam Syafi’i,
“Waman asa ilaika faqod atlaqoka”
(Orang yang berbuat buruk padamu hakikatnya sedang membebaskanmu),
mengajarkan bahwa ketika dicaci, seseorang justru dibebaskan dari ekspektasi manusia.
Dalam konteks rumah tangga pun, ocehan pasangan bisa dianggap sebagai ladang pahala, sementara kemesraan justru terkadang “berbiaya mahal”.

Menemukan Kenyamanan dalam Ketaatan
Maksiat, menurut Gus Baha, seringkali bersumber dari pencarian kesenangan sesaat. Karena itu, seorang Muslim seharusnya belajar menemukan kenyamanan dalam ibadah dan ketaatan. Dalam literatur tasawuf, disebutkan bahwa alam semesta ini bisa menjadi sumber ketenangan—bahkan dari hal-hal yang mengecewakan.
Logika sebagai Benteng dari Maksiat
Untuk menjauhkan diri dari maksiat, tidak cukup hanya dengan ancaman neraka. Gus Baha menekankan pentingnya pendekatan logis. Beliau mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW menanggapi seorang pemuda yang ingin masuk Islam namun meminta izin untuk tetap berzina. Rasulullah tidak langsung melarang, melainkan bertanya dengan logika:
“Apakah kamu senang jika ibumu dizinai? Anak perempuanmu? Bibimu?”
Pertanyaan ini menyentuh nurani si pemuda hingga akhirnya ia membenci zina dan meninggalkannya.
“Logika ini penting, agar kita memiliki harga diri untuk tidak bergantung pada hal-hal yang merusak,” ujar Gus Baha.
Hidup Rileks, Mati pun Tenang
Pola pikir juga memengaruhi cara pandang terhadap kekikiran. Orang kikir sering merasa hidup terlalu lama dan uang sangat penting. Padahal, Rasulullah mengajarkan bahwa:
- Makanan akan menjadi kotoran.
- Pakaian mewah akan rusak.
- Sedekah adalah satu-satunya cara mengabadikan harta.
“Sedekah itu bukan menguras uang, tapi mengabadikannya,” tutur Gus Baha.
Para ulama terdahulu bahkan memandang hidup dan mati dengan santai. Kematian bagi orang baik adalah husnul khotimah, sedangkan bagi pelaku maksiat adalah akhir dari keburukan. Rasulullah SAW sendiri berdoa:
“Allahumma aj’alil hayata ziyadatan li kulli khairin, wal mauta raahatan min kulli syarrin”
(Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan, dan kematian sebagai istirahat dari segala keburukan).
Bahkan perbuatan mubah (yang diperbolehkan) pun bisa bernilai pahala. Sebab, ketika seseorang tidur, misalnya, ia sedang tidak bermaksiat. Ulama menyebut ini sebagai pahala karena tidak melakukan keburukan.
Kebahagiaan Sejati: Hati yang Bersama Allah
Sebagai penutup, Gus Baha kembali menekankan pentingnya melatih diri untuk berbahagia dalam ketaatan. Ini adalah benteng paling kuat dalam menghadapi godaan maksiat. Firman Allah:
“Alaa bidzikrillahi tathmainnul quluub”
(Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram),
menjadi pondasi utama dalam mengelola kebahagiaan sejati—yaitu hati yang senantiasa bersama Allah, dalam keadaan apa pun. (*)
Penulis: Firnas Muttaqin