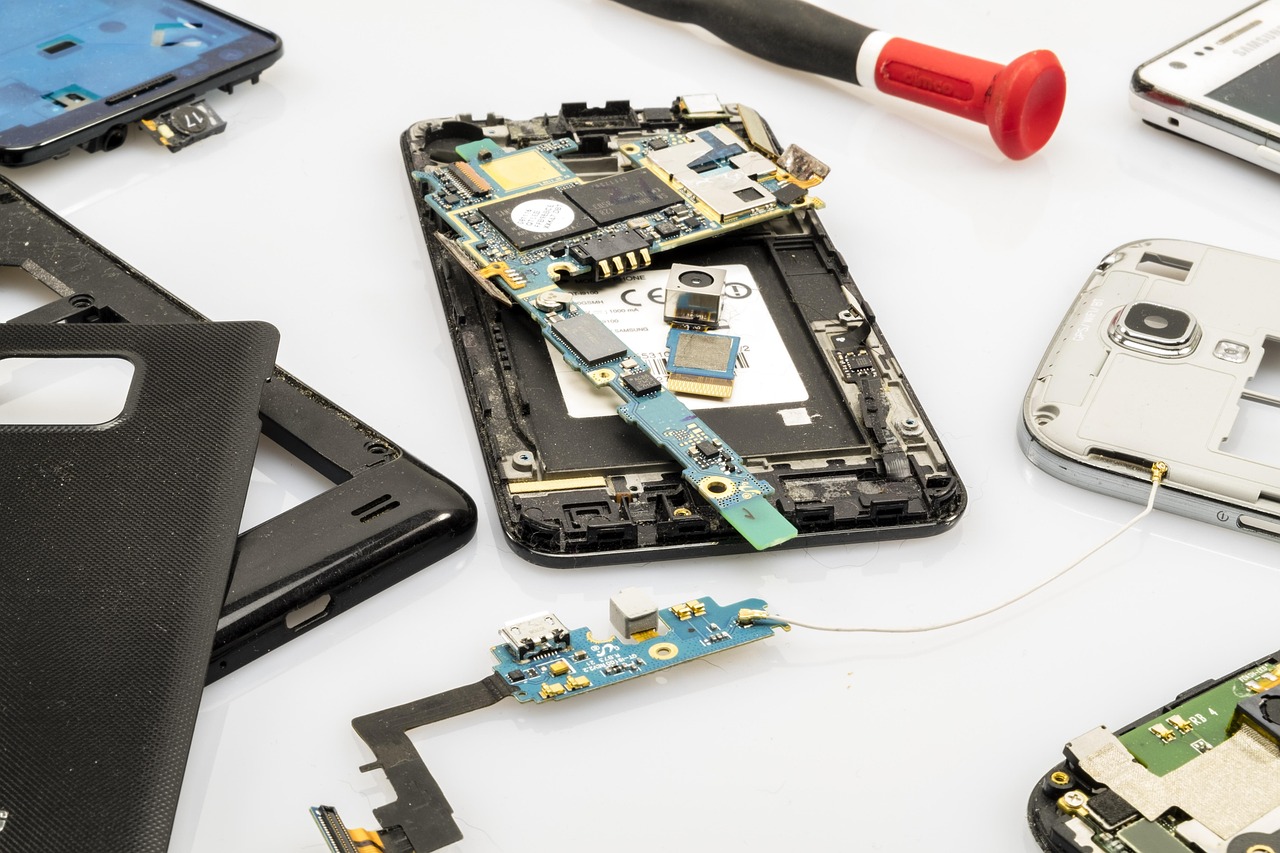Cinta Bisa Menyembuhkan atau Melukai?

Relasi romantis merupakan salah satu bentuk interaksi manusia yang paling kompleks. Di dalamnya, individu tidak hanya berhadapan dengan kebutuhan akan kedekatan emosional, tetapi juga dengan ketakutan akan potensi luka psikologis yang dapat muncul dari keterikatan yang mendalam. Hubungan asmara, dengan segala pasang surutnya, sering kali menghadirkan dilema antara kerentanan dan perlindungan diri, antara hasrat untuk dekat dan dorongan untuk menjaga jarak.
Fenomena ini dapat dipahami melalui kerangka teori keterikatan yang dikemukakan oleh Bowlby (1969). Menurutnya, gaya keterikatan (attachment style) yang terbentuk sejak masa kanak-kanak berperan signifikan dalam membentuk pola pikir, ekspektasi, dan respons emosional individu dalam hubungan dewasa. Misalnya, seseorang dengan avoidant attachment cenderung menampilkan avoidance coping, yaitu strategi menjaga jarak dari pasangan sebagai mekanisme protektif untuk meminimalkan risiko luka emosional. Sebaliknya, individu dengan secure attachment lebih mampu menerapkan approach coping, yaitu menghadapi risiko emosional melalui komitmen, kedekatan, dan komunikasi terbuka. Ketegangan antara dua strategi yang berbeda ini dapat menimbulkan dinamika tarik-ulur dalam relasi, di mana keintiman bisa terasa menenangkan bagi satu pihak tetapi mengancam bagi pihak lainnya (Mikulincer & Shaver, 2016).
Namun, hubungan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intrapersonal. Intervensi sosial juga memainkan peran penting dalam keberlanjutan relasi. Felmlee (2001) menyebut fenomena ini sebagai social interference in relationships, yaitu campur tangan pihak ketiga yang dapat berfungsi sebagai sumber dukungan sekaligus tekanan. Dalam banyak kasus, orang tua, sahabat, atau lingkungan sosial berniat melindungi, tetapi tanpa pemahaman kontekstual yang mendalam, intervensi mereka justru berpotensi kontraproduktif. Tekanan sosial yang menghendaki pasangan berpisah, misalnya, dapat memperburuk konflik internal yang sedang dihadapi, sementara dukungan yang empatik justru dapat memperkuat ikatan pasangan untuk bertahan.
Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pasangan justru tidak mempermasalahkan masa lalu individu. Sikap ini selaras dengan konsep unconditional positive regard dari Rogers (1959), yakni penerimaan tanpa syarat yang diberikan kepada orang lain apa adanya, tanpa syarat tertentu. Penerimaan semacam ini bukan hanya menjadi fondasi kepercayaan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai faktor protektif dalam penyembuhan luka emosional. Farley & Shaver (2023) menegaskan bahwa pengalaman diterima tanpa syarat oleh pasangan dapat menjadi corrective emotional experience yang memungkinkan individu meredakan dampak trauma masa lalu, sekaligus mengembangkan kapasitas untuk membangun keintiman yang lebih sehat.
Meski demikian, penerimaan saja tidak cukup tanpa komunikasi yang sehat. Komunikasi merupakan jembatan utama untuk menyalurkan kebutuhan emosional, menegosiasikan perbedaan, dan mempertahankan keintiman. Salah satu pola yang sering muncul adalah mirroring, yaitu strategi membalas pesan hanya ketika pasangan memulai kontak. Meskipun dapat memberikan kesan kesetaraan, strategi ini berisiko menciptakan stagnasi komunikasi, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan kedekatan emosional. Fitzpatrick & Ritchie (1994) menekankan bahwa komunikasi yang efektif dalam hubungan menuntut keseimbangan antara responsif (mampu menanggapi kebutuhan pasangan) dan proaktif (mampu mengambil inisiatif menjaga kehangatan relasi).
Lebih jauh, penelitian Rogers (1961) menunjukkan bahwa bahasa afektif—yakni ekspresi perasaan secara terbuka dan jujur—lebih efektif dalam menumbuhkan keintiman dibanding bahasa instruktif yang mudah dipersepsikan sebagai kritik. Misalnya, pernyataan “Aku merasa khawatir ketika kamu tidak memberi kabar” lebih mudah diterima daripada “Kamu selalu membuat aku cemas karena tidak pernah memberi kabar.” Penggunaan bahasa afektif dapat mereduksi defensif pasangan dan membuka ruang dialog yang lebih empatik.
Dengan demikian, keberlangsungan hubungan romantis tidak ditentukan semata oleh pengalaman masa lalu maupun risiko sakit hati yang mungkin terjadi di masa depan. Justru, kunci utama terletak pada kemampuan pasangan untuk membangun penerimaan emosional yang tulus dan komunikasi yang hangat. Dalam hal ini, dukungan internal dari pasangan sendiri kerap menjadi faktor protektif yang lebih kuat dibanding tekanan eksternal dari lingkungan sosial. Relasi romantis yang sehat, alih-alih menjadi sumber luka, dapat berfungsi sebagai medium penyembuhan sekaligus ruang pertumbuhan emosional.
Penulis: Lulu